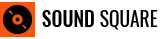Jakarta – Presiden Jokowi akhirnya mencabut sebagian lampiran Perpres No 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bagian yang dicabut adalah lampiran yang mengatur soal investasi produksi dan perdagangan minuman beralkohol. Semula Perpres ini membuka investasi di bidang tersebut di 4 provinsi. Atas desakan sejumlah kalangan, bagian tersebut ditutup. Investasi minuman beralkohol kembali menjadi investasi tertutup.
Apa sebetulnya masalahnya? Protes utamanya berasal dari umat Islam, yaitu MUI, NU, Muhammadiyah, dan banyak organisasi maupun kelompok lain. Apa keberatan mereka? Tentu saja sumber keberatannya adalah minuman beralkohol itu haram. Ditambah, akan merusak generasi muda. Mereka keberatan kalau ada kebijakan “legalisasi miras”.
Poin penting persoalannya ada pada kata kunci itu, yaitu “legalisasi miras”. Seakan ada usaha untuk mengubah sesuatu, dari yang tidak legal menjadi legal. Apa yang tidak legal? Minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol selama ini sudah legal untuk diproduksi dan diperdagangkan. Bahkan pemerintah DKI Jakarta punya saham di pabrik bir, dan mendapatkan dividen dari saham itu setiap tahun. Pemerintah juga memungut cukai dari perdagangan minuman beralkohol.
Jadi apa masalahnya? Perpres yang tujuannya membuka investasi itu dikesankan seolah hendak membuka seluas-luasnya perdagangan minuman beralkohol, membebaskan penjualannya kepada siapa saja. Tentu saja hal itu menimbulkan penolakan.
Tapi bukankah minuman beralkohol itu haram dan pemerintah tak sepatutnya membuka investasi untuk barang haram itu? Kalau soalnya haram, banyak hal yang haram bagi umat Islam. Bunga bank itu haram. Tapi apakah pemerintah harus menutup investasi untuk bank konvensional?
Ada 2 hal penting yang gagal dikomunikasikan Presiden, baik secara langsung maupun melalui para pembantunya. Pertama, bahwa negara ini tidak diatur dengan syariat Islam, melainkan dengan konstitusi dan undang-undang. Kebutuhan umat beragama diperhatikan dalam pembuatan keputusan, tapi dasar pengambilan keputusan bukanlah hukum yang berlaku di suatu agama. Kedua, bahwa pembukaan investasi tidak berarti pembebasan penjualan minuman beralkohol.
Komunikasi soal itu seharusnya dilakukan sebelum Presiden menandatangani Perpres. Seharusnya ada penjelasan kepada pihak-pihak yang berpotensi keberatan. Presiden seharusnya bertanya kepada Wakil Presiden, yang mantan Ketua Umum MUI, atau bahkan menugaskannya untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian penolakan dapat diredam.
Setelah terjadi penolakan, tidak ada upaya penjelasan yang memadai. Yang bergaung adalah pemerintah hendak melegalkan minuman keras. Ini membuat citra Jokowi, yang selama ini oleh sejumlah kalangan dianggap jauh dari umar Islam atau bahkan musuh umat Islam, makin terpuruk. Legalisasi minuman keras bagi mereka adalah bukti betapa buruknya Jokowii. Padahal substansi masalahnya tidak begitu.
Apakah pembatalan itu menyelesaikan masalah? Tidak. Bagi negara ini adalah preseden yang sangat buruk. Sebuah Peraturan Presiden bisa diubah substansinya oleh desakan masyarakat. Presiden tidak serius dalam pengelolaan administrasi negara. Secara politis ini adalah catatan buruk untuk Jokowi. Pembatalan lampiran Peraturan Presiden ini tidak membuat Jokowi tampak seperti seorang presiden yang mau mendengar aspirasi. Ia hanya tampak seperti seseorang yang membatalkan keburukan yang hendak ia lakukan karena ketahuan.
(mmu/mmu)