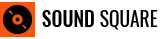Berbagai cara dan modus dilakukan untuk memasukkan ideologi dan paham radikal, intoleransi kepada siswa sekolah. Sungguh sangat memprihatinkan untuk masa depan bangsa. Apa saja modus tersebut? Adakah cara untuk mengatasinya ?
Jakarta – (13/04/2021). Masuknya paham radikalisme di dunia pendidikan menjadi keprihatinan banyak pihak, karena dapat memunculkan tindakan intoleransi pada para pelajar. Direktur Peace Generation Irfan Amalee mengungkapkan indoktrinasi paham radikal itu dilakukan dalam berbagai cara. Maka dari itu, peningkatan pemahaman baik guru dan siswa akan bahaya radikalisme menjadi penting untuk menangkal perkembang-biakannya. Menurut Irfan, ada beberapa narasi dalam perekrutan kelompok-kelompok radikal yang harus dipahami oleh guru dan siswa. Pertama, kelompok radikal biasanya menggunakan narasi politik. “Buat anak-anak yang galau itu mereka melihat ketidakadilan, itu mereka langsung terpanggil untuk jihad,” kata Irfan dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Kedua, kelompok radikal juga menggunakan narasi historis. Menurut Irfan, ini juga perlu diperhatikan oleh para pendidik dalam pendidikan sejarah. “Karena pendidikan sejarah itu bisa saja bukan membangkitkan wisdom, tetapi justru membangkitkan dendam,” imbuh Irfan. Ketiga, narasi psikologis, atau mengglorifikasi tokoh-tokoh kekerasan sebagai pahlawan.
Keempat, instrumental naration atau menganggap kekerasan itu sebagai solusi memecahkan masalah. Terakhir atau kelima adalah narasi keagamaan atau menggunakan ayat-ayat untuk merekrut anggota baru kelompok. “Mereka mencomot, ambil sana-sini sepenggal ayat, kalau anak-anak membaca itu, dan gurunya tidak paham, bisa kalah gurunya. Semakin ingin anak bergabung dengan kelompok radikal. Dan ini cara (perekrutan) yang paling efektif,” ucap Irfan.
Masih rentan
Senada dengan penilaian Irfan, pengamat terorisme Stanislaus Riyanta mengingatkan penanaman sikap radikalisme dan intoleransi di lembaga pendidikan harus dicegah karena anak-anak dan remaja yang masih rentan menjadi target dari propaganda narasi radikal. “Aktivitas dalam lembaga pendidikan yang mengandung narasi-narasi radikal untuk mendorong perilaku intoleran dengan cepat diterima oleh anak-anak,” katanya. Selanjutnya, kata dia, anak-anak tersebut akan menganggap intoleran dan radikalisme sebagai kebenaran dan wajar jika dilakukan sehingga tidak perlu kaget apabila saat ini sudah terjadi aksi terorisme dengan pelaku berusia remaja.
Stanislaus mengingatkan kasus yang baru saja terjadi di Yogyakarta ketika seorang pembina Pramuka dari Gunung Kidul yang menjadi peserta Kursus Mahir Lanjut (KML) Pramuka mengajarkan kepada anak-anak yel-yel dan tepukan rasis yang menyebut kata kafir. Beberapa kasus lain juga hampir serupa, kata dia, misalnya intimidasi dari oknum pengurus Rohis di SMA Negeri 1 di Gemolong, Sragen, kepada seorang siswi karena tidak berhijab. Pernah juga, kata dia, bendera mirip dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikibarkan oleh pengurus Rohis SMK Negeri 2 Sragen di halaman sekolah tersebut. Dia miris menilai kasus-kasus itu sebab paham radikal dan intoleran diajarkan kepada anak-anak di lembaga pendidikan dan menunjukkan bahwa radikalisasi sudah terjadi secara sistematis.
“Pelaku-pelakunya memanfaatkan lembaga pendidikan karena bisa dilakukan dengan intens dengan relasi kuasa dan memanfaatkan kebutuhan figur bagi anak-anak,” katanya menjelaskan. Menurut dia, pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, harus tegas menyikapi hal tersebut sebab propaganda narasi radikal sering kali dikemas sebagai ajaran agama. “Materi-materi pendidikan termasuk ajaran agama harus dipastikan tidak menimbulkan perpecahan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip kebinekaan,” katanya. Dalam dunia pendidikan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, lanjut dia, harus ditegaskan substansi dan materi yang ditransfer kepada anak didiknya bebas dari doktrinasi radikal dan intoleran.
Sikap tegas
Sikap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, kata Stanislaus, patut menjadi rujukan, yakni memberikan peringatan bagi siapa pun yang mencoba memasukkan paham radikal di lembaga pendidikan di Jateng maka sanksi pemecatan siap menanti. Tanpa sikap tegas untuk mencegah maka ruang untuk doktrinasi paham radikal dan sikap intoleran menjadi makin luas. “Jika dalam beberapa tahun ke depan muncul aksi teror oleh remaja, salah satu penyebabnya adalah pemimpin saat ini yang melakukan pembiaran bibit radikalisme tersebut menjadi subur,” katanya.
Sampai tingkat TK
Kenyataan yang lebih memprihatikan adalah temuan organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama, GP Ansor. Baru-baru ini GP Ansor mengklaim beberapa jilid buku pelajaran siswa Taman Kanak-kanak (TK) berjudul Anak Islam Suka Membaca, mengajarkan radikalisme dan memuat kata-kata ‘jihad’, ‘bantai’, dan ‘bom’. Laporan mengenai keberadaan kata-kata dalam beberapa jilid buku itu disampaikan salah seorang ibu di Depok, Jawa Barat, ke GP Ansor setelah anaknya pulang ke rumah dan berbicara mengenai bom dan membantai orang.
“Saya tidak bisa bayangkan apabila kata-kata ini diserap, dihayati oleh anak-anak usia TK. Kemudian 15 sampai 20 tahun ke depan, ada memori dalam alam bawah sadar dia tentang kata-kata itu. Membentuk pandangan yang keras, yang radikal, yang mengabsahkan kekerasan, bom, pembantaian terhadap kyai. Itu kan, dalam pandangan kami, sangat tidak boleh diajarkan pada anak-anak,” kata Sekretaris Jenderal GP Ansor, Adung Abdurrahman, Dalam beberapa jilid buku Anak Islam Suka Membaca, menurut Adung, terdapat setidaknya 32 kalimat yang bisa dipandang radikal. Misalnya, ‘sahid di medan jihad’ dan ‘selesai bantai raih kyai’.
Buku tersebut pertama kali diterbitkan pada 1999 dan telah dicetak ulang sebanyak 167 kali. Edisi ke-167 dirilis pada 2015 dan diterbitkan oleh Pusaka Amanah di Solo, Jawa Tengah. GP Ansor mengatakan buku itu telah menjangkau anak-anak di seantero Indonesia, khususnya anak-anak yang belajar di TK Islam swasta. ”Buku ini karya Nurani Musta’in. Dia istri Ayip Syafruddin yang merupakan pimpinan kelompok Laskar Jihad di Solo,” kata Adung. Menanggapi kata-kata dalam buku Anak Islam Suka Membaca, Kementerian Pendidikan memutuskan untuk melarang penggunaan buku tersebut di sekolah-sekolah.
Peran dalam peperangan
Materi pelajaran sejarah Nabi Muhammad SAW di sekolah dasar dan menengah akan diperbaiki karena cenderung menonjolkan perannya dalam peperangan dan tidak memberi tempat pada sifat-sifatnya yang toleran dan mendukung perdamaian.Kementerian Agama mengatakan, upaya perbaikan ini tidak terlepas dari meningkatnya radikalisasi yang menjangkiti sebagian umat Islam di Indonesia.
Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan pelatihan Kementerian Agama mengatakan, selain menambahkan aspek humanis Nabi Muhammad, pihaknya juga akan memberikan latar belakang kenapa jalan perang yang ditempuhnya. “Kajian kita menunjukkan bahwa sejarah Nabi Muhammad lebih menitikberatkan pada perang-perang, tapi aspek luas tentang sifat nabi yang amanah, jujur, sangat adil, humanis belum banyak di literatur, apalagi literatur di sekolah,” kata Abdurrahman Masud.
Penekanan pada sejarah sosial
Menurutnya, peristiwa sejarah berupa peran Muhammad terkait aspek toleransi dan dukungannya kepada perdamaian sangat penting ditekankan pada situasi “dunia yang berkecamuk” seperti sekarang. “Ada ajaran (Nabi Muhammad tentang nilai-nilai kemanusiaan) yang perlu ditekankan. Jika anak-anak tidak membaca (secara) komprehensif, bisa salah paham,” katanya. Abdurrahman tidak memungkiri kajian ulang terhadap materi sejarah Nabi Muhammad tidak terlepas dari meningkatnya radikalisasi yang menjangkiti sebagian umat Islam di Indonesia. “Ideologi pemerintah ‘kan ideologi kerukunan. Otomatis, kita harus berupaya bagaimana menangkal radikalisme, terorisme,” katanya.
“Pelurusan itu harus, misalnya makna jihad yang disalahpahami, yang selalu diidentikkan dengan perang. Padahal maknanya luas,” tambahnya. Ditanya kenapa selama ini materi pelajaran sejarah Muhammad lebih memberi porsi besar pada perannya di kancah peperangan, Abdurrahman mengatakan, hal ini juga dialami materi sejarah umum.
“Ini yang harus diubah, dengan ditekankan pada sejarah sosial, seperti karakter Nabi yang mulia seperti tertera dalam Kitab suci serta sejarah yang sebagian ditulis oleh non-Muslim,” jelasnya.
Tergantung bahan yang diterima
Direktur Lembaga kajian Islam dan perdamaian (LAKIP) Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bambang Pranowo mendukung rencana Kemenag tersebut supaya “gambaran tentang Nabi Muhammad lebih utuh.” “Bahwa Nabi itu pembawa rahmat itu harus lebih menonjol sehingga tidak malah terkesan pembawa laknat,” katanya. Rencana Kemenag untuk memberi porsi lebih besar pada sifat-sifat Muhammad yang toleran dan mendukung perdamaian, menurutnya, juga relevan untuk situasi sekarang. Empat tahun lalu, temuan survei LAKIP terhadap pelajar SMP-SMA di 100 sekolah (59 swasta, 41 negeri) menunjukkan hampir 50% pelajar setuju dengan “cara-cara kekerasan dalam menangani isu moralitas dan keagamaan”.
“Kalau penyebab secara spesifik, harus diteliti lebih dalam, tetapi bisa diduga karena memang bahan-bahan yang mereka terima mengarah pada hal tersebut,” papar Bambang. “Misalnya saja dalam pendidikan agama, kurang sekali memberi penekanan kepada Nabi sebagai pembawa perdamaian itu, maka kemudian ketika timbul literatur tentang kehidupan Nabi cenderung yang pada kekerasan, itu mudah sekali masuk,” jelasnya lebih lanjut.
Dia kemudian memberikan contoh, kehadiran literatur-literatur seperti itu yang dikeluarkan oleh kelompok radikal. “Apalagi kondisinya memungkinkan anak didik kecewa dengan keadaan, sehingga ketika ada wacana tentang hal yang menuju pada kekerasan, atau mengubah keadaan dengan kekerasan, itu mudah sekali masuk dan mudah dicerna,” jelasnya.
Komentar Guru Agama Islam
Sementara itu, seorang guru agama Islam di SMA Negeri II, Malang, Jatim, Muniron mengakui bahwa dalam sejauh ini pelajaran sejarah Nabi Muhammad lebih menitikberatkan pada perannya dalam sejumlah peperangan, walaupun aspek lainnya juga dibahas. “Sepertinya begitu, tapi ya adalah aspek pribadi kanjeng Nabi,” kata Muniron. Dia sendiri mendukung langkah Kemenag untuk menambahkan sejarah Muhammad terkait aspek toleransi atau perdamaian. “Kita tidak bisa menampik adanya peperangan dalam sejarah Islam, cuma harus bisa kita kemas lagi supaya tidak begitu terlalu nampak kasarnya,” katanya.Hal itu dia tekankan karena setiap peperangan itu tidak terlepas dari alasan kemunculannya. “Misalnya untuk menjaga diri,” kata Muniron.
Lebih lanjut dia mengatakan, penekanan pada aspek humanis Nabi Muhammad itu menjadi penting ditekankan dalam situasi sekarang. “Kalau peperangan kita ‘kan cuma pasif melihatnya, tapi kalau kita tampilkan pribadi kanjeng yang menghormati orang atau kelompok lain, itu bagus ditambahkan dalam materi sejarah,” katanya.
Ihtiar pencegahan
Berbagai ihtiar pencegahan menyebarkan benih radikalisme di tingkat pendidikan sekolah mutlak harus terus dilakukan. Menurut Satriwan Salim, Pengajar di Labschool Jakarta-UNJ dan Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI) mengatakan, peristiwa bom Surabaya dan Makassar yang terjadi baru-baru ini menimbulkan fenomena baru dalam kajian terorisme. Fenomena baru itu adalah keterlibatan satu keluarga termasuk anak-anak dalam aksi terorisme, dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Anak-anak yang terlibat nota bene merupakan siswa berusia sekitar 8-18 tahun, yaitu usia sekolah.
Temuan yang lebih mengerikan lagi, lanjut dia, adalah intoleransi dan bibit-bibit radikalisme sudah masuk dan berkembang di sekolah-sekolah. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017), dilakukan terhadap siswa/mahasiswa dan guru/dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3 persen responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam. Kemudian, sebanyak 48,95persen responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi 58,5 persen responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal.
Persoalan yang muncul, mengapa bibit-bibit radikalisme bisa masuk ke sekolah? Dan bagaimana strategi sekolah agar mampu mencegah pemahaman radikalisme memengaruhi cara berpikir guru dan siswa? Menjawab pertanyaan pertama di atas, sudah banyak kajian dilakukan oleh banyak lembaga terkait intoleransi, antikebinekaan dan bibit-bibit radikalisme yang mulai masuk ke ranah persekolahan. Semua lembaga relatif sepakat jika radikalisme yang masuk ke sekolah melalui; (1) aktivitas pembelajaran di kelas oleh guru, (2) melalui buku pelajaran yang diduga memuat konten intoleransi, (3) melalui pengaruh dan intervensi alumni dalam kegiatan kesiswaan di sekolah dan (4) lemahnya kebijakan kepala sekolah/yayasan dalam mencegah masuknya pengaruh radikalisme.
Guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran dan jenjang sekolah tempat mengajar, semestinya paham, bahwa mereka adalah insan pedagogis yang sedang melakukan aktivitas kebangsaan, berlomba-lomba mencapai tujuan bernegara. “Tapi kenyataannya terbalik, ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk memusuhi negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaannya. Mengatakan bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada bendera merah putih adalah haram atau bid’ah bahkan ada oknum guru yang terlibat aktif menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” tutur Satriwan.
FSGI (Federasi Serikat Guru Indonesia) menemukan ada guru yang bersimpati bahkan mendukung “perjuangan” organisasi teroris ISIS di Timur Tengah. Dan rasa simpatinya tersebut disampaikan di depan kelas. Ada juga guru yang terang-terangan mempromosikan organisasi HTI di depan kelas; mempertanyakan eksitensi Pancasila, mempromosikan ide negara khilafah dengan segala doktrinasi HTI lainnya. Ini ditemukan di salah satu sekolah negeri di Bogor. Juga ada laporan bahwa ada guru di Batam, yang tidak mau hormat kepada bendera merah putih di saat upacara bendera. Padahal guru tersebut sedang menjadi pembina upacara. Sikap seperti itu sudah sering ditunjukkannya di depan siswa & guru lain.
Pembelajaran minus nalar
Kemudian nilai intoleransi juga muncul di pembelajaran, ketika guru tidak mampu mendisain pembelajaran yang menggugah nalar siswa; pembelajaran kritis (critical thinking & critical pedagogy) dan problem based learning. Pembelajaran kita belum terbiasa dengan pergulatan ide, perdebatan dan argumentasi yang baik. Semua itu cerminan keterampilan berpikir kritis, yang lazim dikenal HOTS (Higher Order Thinking Skill). Pembelajaran kita baru terbiasa dengan ceramah, satu arah dari guru. Pembelajaran yang memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi guru untuk bermonolog. Sehingga pembelajaran dengan “student centered learning” tak terpakai dengan baik.
Para siswa kita hanya dibiasakan menjawab soal-soal kelas rendah, berupa pilihan ganda (PG) belaka. Keterampilan berpikir masih tingkat rendah (lower order thinking skill); mengingat, menghafal dan memahami. Berhenti pada jenjang memahami sebuah teks atau peristiwa. Belum bergerak naik mengaktifkan keterampilan berpikir tingkat tinggi; menganalisis, membandingkan, mengkomunikasikan, mengkritisi, problem solving dan berkreasi (HOTS).
Belum terkonstruksinya desain pembelajaran berbasis critical thinking di atas, diawali oleh belum terbiasanya guru mendengarkan argumentasi siswa, guru tahu segalanya sedangkan siswa tidak tahu, guru selalu benar, guru adalah sumber belajar satu-satunya. Akibatnya adalah siswa menjadi inferior di hadapan guru. Siswa takut bicara dan menyampaikan pendapatnya secara terbuka di depan kelas. Bahkan jika pun ada siswa yang kritis, maka akan dianggap kurang sopan. Sekolah kurang memberikan ruang aktualisasi diri kepada siswa. Pola-pola seperti itulah yang masih lazim terjadi di dunia persekolahan kita. Seperti yang pernah dikeluhkan dan dikritik oleh Soe Hok Gie (1942-1969) bahwa, “guru bukanlah dewa, dan murid bukanlah kerbau yang dicocok hidungnya.”
Makanya pedagog seperti Ivan Illich (1926-2002) menerbitkan tulisan kontroversialnya berjudul “Deschooling Society” (1970) sebagai bukti bahwa institusi pendidikan dan sekolah abad XX sudah bobrok. Lembaga sekolah secara terencana mengalienasikan anak didik dari diri dan lingkungannya. Pun kumpulan tulisan berjudul “Sekolah itu Candu” (1998), yang ditulis Roem Topatimasang bahwa pendidikan dan persekolahan kita memang sudah rusak, sampai kepada praksis pembelajarannya di kelas.
Strategi Pencegahan Radikalisme di Sekolah
Jika demikian faktanya, bagaimana strategi kita agar sekolah, guru dan pembelajaran di kelas tidak lagi memberi ruang bagi penyemaian virus intoleransi dan radikalisme? Menjawab pertanyaan ini, Satriwan menyampaikan, Pertama, guru harus mentransformasikan dirinya menjadi pendidik yang benar-benar mendidik. Pendidik yang tak lepas dari misi kebangsaan; mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua guru mata pelajaran harus diberikan wawasan kebangsaan yang baik. Guru adalah role model bagi siswa. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa diwujudkan oleh siswa, jika role model-nya saja justru memperlihatkan sebaliknya.
Kedua, mau tidak mau para guru mesti menyegarkan keterampilan mengajarnya. Kewajiban pemerintah sebenarnya untuk memenuhi tuntutan ini. Praktik pembelajaran yang menarik, kreatif, berpikir kritis dan berpusat pada siswa. Inilah tantangan yang mesti dilakukan guru sekarang. Apalagi yang diajar adalah Generasi Z, yang bahasa zamannya berbeda dengan gurunya yang berasal dari Generasi X bahkan sebelumnya. Tinggalkan pembelajaran yang memberi ruang superioritas bagi guru. ”Guru jangan lagi mendoktrin di depan kelas. Mendidik itu bukan proses doktrinasi. Tapi proses pembangunan karakter melalui argumen & dialog. Bukan melalui monolog!,” tegasnya.
Ketiga, berdasarkan diagnosis masuknya bibit radikalisme ke sekolah di atas, kepala sekolah/ketua yayasan berperan penting melakukan pembinaan kepada guru yang sudah kadung intoleran bahkan radikal. Kepala sekolah harus memetakan pemahaman “ideologis” para guru. Apalagi bagi calon guru, misalnya di swasta. Rekrutmen guru baru tidak hanya mensyaratkan empat (4) kompetensi guru, tetapi menambahnyaa dengan kemampuan (keterampilan) wawasan kebangsaan guru.
Termasuk pemantauan konten pembelajaran guru di kelas. Bisa dikroscek pada siswa. Siswa pun harus berani melaporkan kepada wali kelas/kepala sekolah jika ada guru mengajarkan intoleransi di kelas. Siswa jangan sungkan apalagi takut menyampaikan/memprotes (tentu dengan adab yang baik). Triangulasi informasi antara kepala sekolah, wali kelas dan siswa (orang tua) harus dilakukan kontinu. Kepala sekolah juga mesti ketat dan tegas dalam membuat kegiatan kesiswaan. Keterlibatan alumni dan orang luar tak masalah, asalkan kepala sekolah/wakil sudah mengetahui profil alumni/pembicara luar tersebut. Ruang aktivitas dan kreativitas siswa mutlak harus ada, tetapi dengan kontrol yang baik dari sekolah. Agar doktrin radikalisme tidak terinfiltrasi masuk melalui pihak luar tersebut.
Keempat, yang tak kalah penting adalah sudah waktunya bagi Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) Kemdikbud membuat “model pembelajaran” bermuatan pencegahan radikalisme, intoleransi dan terorisme bagi semua guru mata pelajaran & jenjang. Termasuk pelatihan yang berjenjang, berkelanjutan dan berkualitas. Karena tugas untuk mencegah radikalisme di sekolah itu bukan hanya tugas guru PPKn/PKn dan Pendidikan Agama saja, tapi tugas pokok semua guru.
Aqidah dan Syariah
Masih berkaitan dengan mencegah radikalisme. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta dosen agama di fakultas umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan Aqidah dan Syariah. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan risiko peningkatan radikalisme. “Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup dua kali pertemuan. Rukun iman dan [rukun] islam,” Said Aqil.
“Kecuali [jurusan] ushuluddin, kecuali [jurusan] fiqih atau tafsir hadis. Itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas yang umum, seperti teknik, hukum misalkan enggak usah banyak-banyak tentang aqidah dan syariah, cukup dua kali,” tuturnya. “Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya, surga-neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu radikal jadinya,” ucap dia. Berdasarkan Quran dan Hadist, Said Aqil menjelaskan bahwa manusia tidak hanya ditugaskan untuk melakukan hal-hal terkait teologi atau ‘ilahiyah’ , tetapi juga menyangkut kemanusiaan.
“Agama bukan dari langit, tapi dari manusia sendiri,” jelasnya. Ia memberi contoh, seharusnya dosen-dosen harus mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam. Delapan abad yang lalu, kata dia, intelektual Islam lebih maju dari Eropa dan China. “Waktu itu Eropa masih tidur, China masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa,” ucapnya. “Bagaimana para ulama para pemikir para teknokrat sudah mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa,” tambah dia.
Untuk itu, dia mengingatkan kembali agar para dosen, terutama dosen dari kalangan PMII dan NU untuk memperluas keilmuan di luar keagamaan juga. Selain itu juga ia mendorong agar terus berinovasi bukan hanya sekadar melakukan rutinitas mengajar biasa.
Dua paham ekstrem
Terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) terbesar bagi bangsa Indonesia guna menangkal penyebaran paham radikalisme. Menurutnya, saat ini Indonesia terjebak dalam dua paham ekstrem, yakni ekstrem liberal dan konvensional. Oleh karena itu, perlu ada moderasi yang masif. “Soal moderasi beragama, ini menjadi PR besar kita, bukan hanya PR besar Kemenag, tapi juga PR bangsa dan negara ini,” kata Yaqut.
Sependapat dengan itu, Mantan Kepala BNPT, Ansyaad Mbai menyimpulkan, gerakan ekstremisme saat ini bermain di dua kaki. Keduanya yaitu jalan kekerasan, yakni terorisme, dan jalan politis lewat seruan atau narasi yang pro-ekstremisme. Ia menyebut contoh seperti gerakan politik yang digelorakan kelompok 212, yang menjadi bagian dari dinamika politik praktis sejak beberapa tahun lalu. Menurut Ansyaad, narasi turunan pro-ekstremisme yang mudah dideteksi paling tidak ada empat parameter, yakni narasi khilafah, konsep hukum Tuhan, takfiri atau pengafiran, jihad (dalam arti kekerasan), serta ”hijrah”—yang dahulu dimaksudkan pergi ke Suriah bergabung dengan NIIS.
Narasi-narasi turunan itulah yang tak hanya kerap dikobarkan oleh pihak-pihak di level elite, tetapi juga menyusup hingga ke dalam berbagai kelompok-kelompok kecil kajian keagamaan yang berhaluan puritanisme, yang jamak diikuti keluarga-keluarga. Apalagi di tengah tren ”hijrah” di keluarga muda di kawasan urban saat ini. Tanpa mengatasi diseminasi ideologi pro-ekstremisme oleh pihak-pihak elite tersebut, sel-sel keluarga bisa terus bermunculan. Awalnya sekadar teradikalisasi sekeluarga, lama-lama sekeluarga bermain di garis depan aksi teror. Di level keluarga inilah instrumentalisasi agama dalam gerakan terorisme menjadi lebih solid. Lantas bagaimana bisa dalam negara yang mengusung demokrasi, narasi demikian bisa dihadang? Konsep kebebasan dalam demokrasi, menurut Ansyaad, memang menemui ujian krusial. Gerakan ekstremisme, termasuk yang mengusung jalan teror, selama ini justru sukses berkembang biak di suatu negeri dengan memanfaatkan iklim demokrasi yang memberi pengakuan universal yang setara akan eksistensi semua manusia dengan latar belakang apa pun.
Sementara, bagi kelompok ekstrem demokrasi itu sendiri serupa jalan setan, yang tak dikehendaki Tuhan. Ansyaad berargumen, apakah adil membiarkan diseminasi narasi pro-ekstremisme yang ternyata terbukti berakibat pada terampasnya kemanusiaan dan terancamnya koeksistensi sesama manusia?
Begitulah, paham ekstrem memang harus terus dipandau dan dideteksi sedini mungkin. Memang tidak mudah meredam semuanya. Namun apabila pemerintah, penegak hukum, TNI-Polri tetap tegas merespon setiap narasi ekstrem dan radikal, maka kejadiannya akan bisa segera kita antisipasi. Organisasi yang dinilai ekstrem boleh saja dibubarkan, namun faktanya ideologi tak bisa dibunuh. Untuk itu paling tidak upaya yang bisa kita lakukan adalah mengeliminir konten-konten atau narasi yang berkenaan dengan khilafah, takfiri, hijrah yang bisa kita lihat sebagai indikator benar-benar dibatasi ruang geraknya, sambil sekaligus meningkatkan sosialisasi ajaran Islam moderat dan rahmatan lil alamiin di berbagai tingkat atau kelompok masyarakat. (Saf).